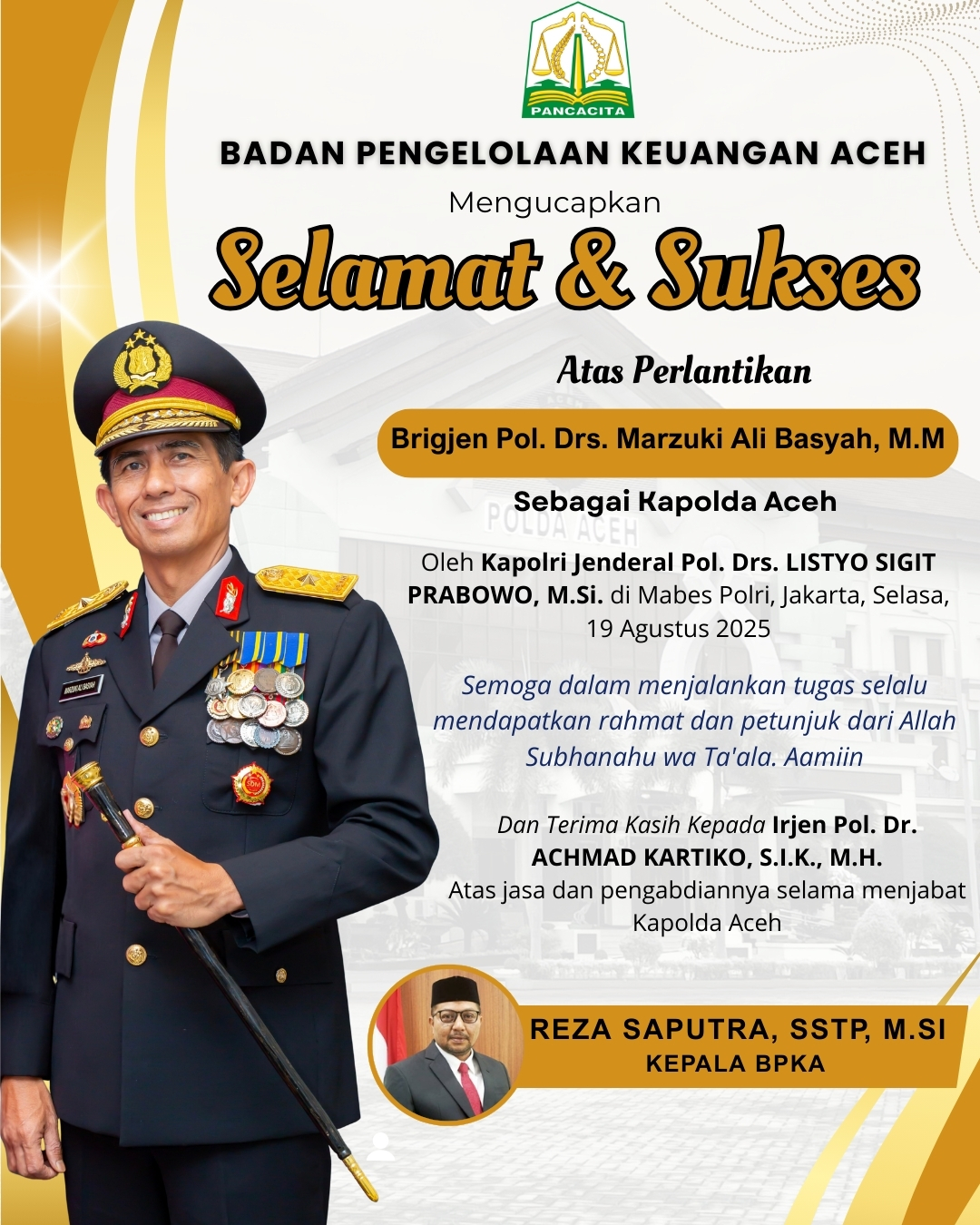Kedua, pemberdayaan dan perlindungan yang inklusif. Hal ini penting sekali dan memperkat dengan poin pertama di atas, yang jika dilihat dalam materi qanun saat ini belum ada penormaan yang menempatkan strategi ‘social inclusion” dimaksud. Padahal, posisi perempuan dengan suku, agama, ras, kelas-status sosial, pilihan politik, mayoritas-minoritas, cenderung mengalami persoalan yang tidak sama dan cenderung pula diperlakukan secara berbeda. Misalnya, perempuan dengan suku minoritas atau menganut agama yang bukan mayoritas, berpeluang besar tidak mendapatkan akses terbuka dalam agenda pemberdayaan dan perlindungan perempuan! Oleh karena itu, poin pertama dan kedua mesti menjadi filosofi mendasar dalam membangun kerangka materi qanun ini ke depan.
Ketiga, strategi dan mekanisme pemberdayaaan dan perlindungan. Dalam Qanun PPP, penulis tidak menemukan ada kejelasan sebenarnya strategi dan mekanisme seperti apa yang dijalankan oleh Pemerintah Aceh dan juga Pemerintah Kab/Kota di Aceh untuk memastikan pemberdayaan dan perlindungan perempuan tersebut berjalan efektif dan berkesinambungan. Padahal inilah yang harus diperjelas dengan pembagian peran yang terukur. Oleh sebab itu, rumusannya harus secara eksplisit mencantumkan strategi dan mekanisme dimaksud.
Keempat, jaminan alokasi anggaran yang memadai. Salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah minimnya alokasi anggaran untuk PPP. Bayangkan, pagu anggaran yang dikelola oleh lembaga ini saja secara keseluruhan sangat kecil. Pada tahun 2008, BPPPA Aceh hanya mengelola anggaran sebesar Rp 14,5 milyar, yang sudah termasuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Bandingkan dengan kondisi dalam beberapa tahun terakhir ketika Badan menjadi Dinas, trend pagu anggaran BPPA Aceh/DPPPA Aceh sejak tahun 2008 s.d 2016 mencapai Rp. 145,3 milyar atau rata-rata hanya sebesar Rp 16,15 milyar per tahun, termasuk didalamnya untuk belanja pegawai.
Alokasi dana tersebut sangat kecil dibandingkan dengan kompleksitas urusan yang ditangani. Di sini harus diakui, ada tantangan antara kebutuhan dan persoalan yang dihadapi dengan kapasitas dan manajerial organisasi dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran. Bagaimana minimnya alokasi anggaran tersebut disikapi? Hal ini harus dicermati kembali dalam penormaan qanun yang baru, tidak lagi sebatas penormaan yang ada dalam Pasal 5 dari qanun yang ada saat ini. Apakah perlu mencantumkan prosentase minimal misalnya, atau ada cara lain yang harus disebutkan secara eksplisit sehingga agenda ini nyata sebagai prioritas. Tentu hal ini perlu dikaji secara khusus dari aspek hukum dan kapasitas fiskal daerah.
Kelima, memperkuat dukungan lintas sektor baik komponen pemerintah maupun non pemerintah. Hal ini menjadi penting sekali bukan hanya di tingkat provinsi tetapi juga di kab/kota di Aceh. Bahkan dengan adanya UU Desa, membangun kontribusi Pemerintahan Gampong untuk berpartisipasi dalam agenda pemberdayaan dan perlidungan perempuan sangat mungkin dilakukan. Dalam Qanun PPP, hal demikian belum ada pengaturannya sehingga terkesan qanun tersebut hanya milik dan tanggunjawabnya DPPPA Aceh.
Keenam, menghubungkan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dalam dokumen perencanaan lintas SKPA sehingga menjadi arus-utama (mainstreaming). Sebagai salah satu urusan wajib nonlayanan dasar dengan capaian IPG dan IDG yang ditargetkan, tidak akan mungkin DPPPA bisa melakukannya sendiri jika ini tidak menjadi perhatian lintas sektor. Oleh sebab itu, perlu dipetakan SKPA mana saja yang bersinggungan langsung dengan isu ini khususnya yang relevan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Sebab, salah tujuan SDGs yakni dengan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, yang mestinya menjadi perhaian bersama untuk mencapainya.
Ketujuh, kebijakan khusus untuk memperkuat kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) di DPPPA Aceh. Pengalaman menunjukkan regulasi seideal apapun menjadi kurang bermakna tanpa dukungan kelembagaan dan SDM yang mumpuni. Penting dipertimbangkan dalam rumusan qanun seperti polaa penempatan pejabat dengan kriteria tertentu hingga penguatan tatakelola organisasinya. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa jika para pejabat yang menangani urusan ini baik di tingkat provinsi maupun kab/kota tidak memiliki perspektif yang baik dan benar terkait isu ini, dapat dipastikan kerja-kerja pemberdayaan dan perlindungan perempuan yang on the track hanya ada di atas kertas. Bila pejabatnya tidak memiliki passion dengan mandatory DPPPA, bisa jadi cara kerjanya pun berlawanan dengan semangat yang diperjuangkan oleh dinas ini. Artinya, perlu dikaji bagaimana mengatur mekanisme mutasi, rotasi, dan promosi pejabatnya sehingga semangat perubahan dapat direalisasikan secara optimal termasuk agenda penguatan kapasitas internal secara terencana.
Kedelapan, sejumlah perlakukan khusus atau afirmasi. Poin ini sebenarnya sudah dibuka jalannya dalam Pasal 25 dalam Qanun PPP dengan mencantumkan penegasan “Untuk mempercepat upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan, Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota wajib melakukan kebijakan-kebijakan bersifat khusus”. Hanya saja, karena materi qanun sangat sederhana sehingga tidak dijelaskan kebijakan seperti apa yang dimaksudkan. Pada bagian Penjelasan qanun pun dicantumkan “cukup jelas” yang setiap pembacanya pasti meraba-raba, apa yang dilakukan dengan kebijakan bersifat khusus itu.
Setidak-tidaknya, kebijakan afirmasi tersebut perlu dicantumkan seperti pemilahan hak perempuan dengan latar yang berbeda. Ke depan, selain mempertegas hak-hak perempuan secara umum, juga perlu dirincikan seperti hak perempuan penyandang disabilitas dan hak perempuan korban kekerasan. Begitupun dengan pemberdayaan, harus jelas selain mengatur pemberdayaan secara umum, juga ada pemberdayaan spesifik seperti perempuan kepala keluarga, perempuan pasca perceraian, dan perempuan dalam masa rehabilitasi pasca bencana.
Mencermati kondisi kab/kota yang berbeda, penting dipertimbangkan membangun skema afirmasi berbasis wilayah. Artinya, perlu perhatian khusus pada kab/kota yang kritis dan membutuhkan intervensi lebih kuat dari Pemerintah Aceh. Misalnya, kab/kota yang semakin tinggi angka kekerasan, tingkat KDRT makin tinggi, capaian IPG dan IDG terus menurun, atau terkena dampak bencana yang butuh penanganan ekstra, maka diatur dalam qanun untuk menjadi prioritas dukungan program pemberdayaan dan perlindungan perempuan dari Pemerintah Aceh.
Kesembilan, akses perempuan menjadi pemimpin. Inilah salah satu tantangan berat yang dihadapi perempuan di Aceh saat ini. Meskipun dalam bagian Penjelasan Qanun PPP diuraikan bukti sejarah kepemimpinan perempuan sebagai Ratu (beturut turut yaitu Sultanah Safiyatuddin Syah, Sultanah Zakiyatuddin Syah, Sultanah Kamalatsyah dan Sultanah Inayat Syah) dan menguraikan sosok Laksamana Malahayati, Cut Nyak Dhien, Cut Meutia, dan Pocut Meurah Inseun bahwa perempuan di Aceh tempo doelo memiliki kualitas dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam rangka memperjuangkan dan mengatur tatanan kehidupan, dalam kondisi sekarang malah yang terjadi sebaliknya.
Bayangkan, perempuan yang mencalonkan diri sebagai Geuchik saja, begitu berat tantangn perempuan apalagi menjadi pemimpin pada posisi yang lebih strategis. Oleh sebab itu, materi terkait akses menjadi pemimpin ini penting dikaji kembali dalam ruang publik yang lebih luas. Bukan hanya terbatas pada jabatan politik di lingkungan eksekutif dan legislatif (partai politik), dan jabatan pekerjaan seperti yang ada dalam Qanun PPP saat ini.
Kesepuluh, partisipasi masyarakat dan bentuk apresiasi. Pengaturan tentang partisipasi masyarakat perlu ditinjau ulang karena penormaan yang ada tidak jelas maksudnya. Dalam Pasal 24 pada ayat (1) setiap anggota masyarakat berhak memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Selanjutnya pada ayat (2) setiap anggota masyarakat berhak memperoleh atau memberikan informasi pelanggaran hak-hak perempuan, sedangkan pada ayat (3) masyarakat berhak menyampaikan saran dan pendapat dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Rumusan terebut jelas ambigu dan bercampur antara hak dengan bentuk partisipasi yang diharapkan.
Selain persoalan partisipasi, hal yang belum ada yakni pengaturan terkait penghargaan atau apresiasi. Bagaimana memberikan penghargaan kepada para pihak yang dianggap mendukung atau berkontribusi dalam agenda pemberdayaan dan perlindungan perempuan? Saat ini, dengan semakin menguatnya dorongan kerja-kerja kolaboratif lintas pihak, apresiasi menjadi sebuah terobosan yang perlu dibudayakan. Hal ni akan memperkuat energi DPPPA Aceh karena semakin banyak pihak yang ikut mendukung kerja-kerja pemberdayaan dan pelindungan perempuan di Aceh.
Kesebelas, penegasan batas waktu pembentukan peraturan pelaksana. Sebuah qanun sering sekali tidak bisa berjalan maksimal karena peraturan pelaksananya berupa Peraturan Gubernur yang tidak kunjung ditetapkan. Dalam Qanun PPP, penegaasan itu tidak ada sehingga ada tidaknya peraturan pelaksana itu sangat tergantung pada komitmen DPPPA Aceh sebagai leading sector. Ke depan, perlu ada ketentuan peralihan yang mengunci batas waktu kapan peraturan pelaksana harus ditetapkan sehingga qanun menjadi dokumen yang lebih hidup, bukan dokumen mati.
Mulai dari Sekarang!
Sebagai penuutup, inisiasi mendorong pergantian Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tersebut dapat dimulai dengan membaca kembali “Piagam Hak-Hak Perempuan di Aceh”. Piagam yang ditandangani pada 11 November 2008 itu memuat banyak penegasan akan komitmen daerah untuk memenuhi hak-hak perempuan di berbagai bidang pembangunan di Aceh. Terlepas apakah prosesnya akan diajukan oleh eksekutif atau menggungakan jalur hak insiatif parlemen (DPRA), harapannya proses tersebut sudah berjalan dan qanun ini sudah ada yang baru sebelum Pilkada serentak dilaksanakan dan sebelum Gubernur definitif terpilih.
Sekali lagi, prosesnya perlu disegerakan agar qanun yang baru dapat menjadi acuan dalam perencanaan DPPPA Aceh pada tahun mendatang, termasuk dalam mempersiapkan materi yang akan dimasukkan ke dalam dokumen RPJMA pada periode mendatang. Prosesnya tentu akan membutuhkan waktu, apalagi Program Legislasi Aceh (Prolega) Tahun 2023 sudah ditetapkan yang minus pengusulan revisi Qanun PPP ini. Namun demikian, tidak salahnya apabila DPPPA Aceh segera menginisiasi proses evaluasi secara menyeluruh dan kemudian menyusun Naskah Akademik yang berkualitas. Naskah Akademik sebagai kerangka berpikir yang argumentatif, menyajikan data dan informasi, serta rumusan pengaturan yang diperlukan untuk merespon sebuah kondisi atau menciptakan kondisi ideal yang dicitakan.
Akhir kata, semoga tulisan ini dapat menjadi bagian dari menjaga kualitas partisipasi publik untuk mendorong terbentuknya “koalisi bersama” untuk percepatan agar Qanun PPP yang baru segera terwujud. Tidak ada pilihan lain selain membangun gerakan yang solid antara komponen masyarakat sipil - gerakan perempuan, DPPPA Aceh, DPRA terutama anggota legislatif perempuan, kalangan kampus, cendekiawan, jaringan media, tokoh adat dan tokoh agama yang punya komitmen yang sama untuk urusan ini. Gerak bersama ini akan memberikan kita harapan baru untuk memberdayakan dan melindungi perempuan secara lebih bermartabat di Aceh.***

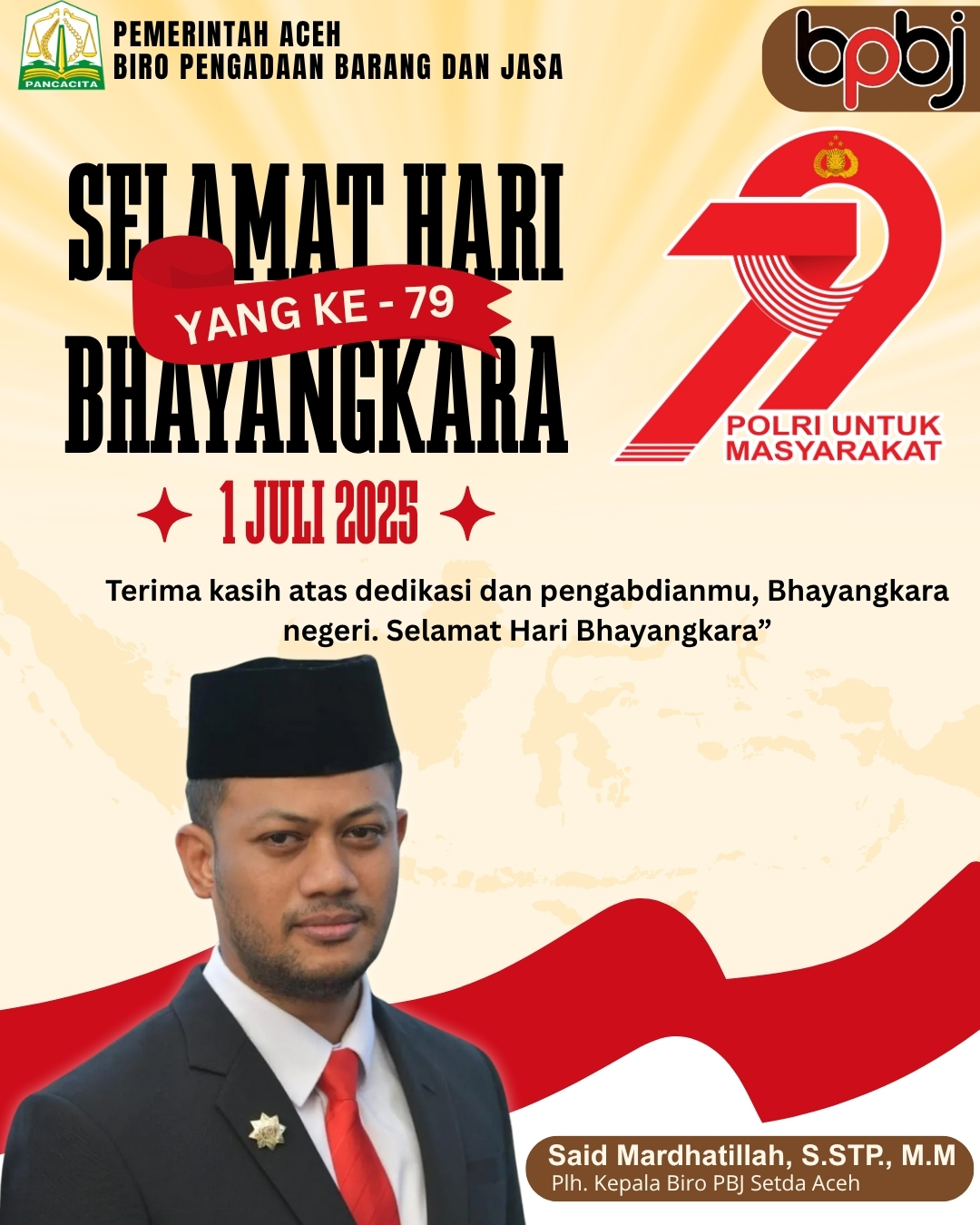
.jpg)
.jpg)