Analisis Filosofis Kebijakan Publik di Aceh terhadap Tujuan Penguatan Syariat Islam
Font: Ukuran: - +
Penulis : Satria Gunawan
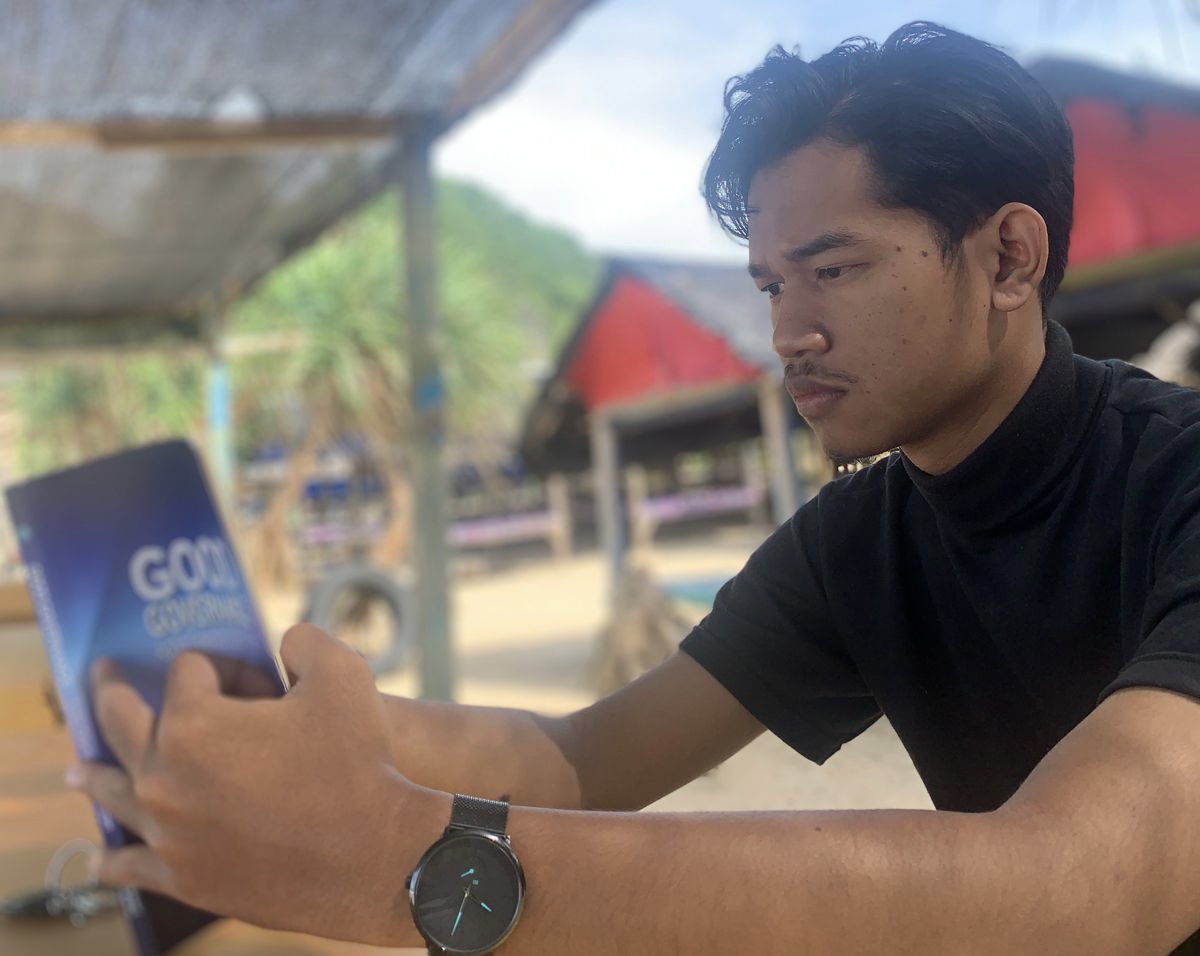
DIALEKSIS.COM | Opini - Seperti halnya dalam kehidupan sehari-hari, berpikir adalah hal yang mendahului segala hal dari setiap tindakan yang akan dilakukan. Begitu pula dalam proses penetapan sebuah kebijakan, kebijakan yang baik adalah sebuah kebijakan yang lahir dari proses berpikir filosofis yang panjang dan penuh kehati-hatian sebelum ditetapkan, sebab hal ini berkaitan dengan kepentingan orang banyak.
Kebijakan publik tidak hanya menjadi instrumen untuk menyelenggarakan kepentingan publik, tapi sudah harus menjadi bagian yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kebijakan mempunyai tujuan menyelesaikan persoalan yang ada secara tuntas, bukan menyelesaikan persoalan dengan menimbulkan persoalan baru, maka dari itu kebijakan publik hendaknya menjadi solusi terhadap persoalan yang tengah dihadapi oleh masyarakat.
Belakangan, pemerintah Aceh membuat suatu kebijakan dengan mengeluarkan SE Pj Gubernur yang mengatur penguatan dan peningkatan pelaksanaan syariat Islam bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat di Aceh yang menimbulkan pro-kontra. Terlepas dari kedudukannya sebagai kebijakan yang terikat atau tidak, pengeluaran SE ini sudah termasuk dalam proses penetapan kebijakan publik, sebab SE ini diarahkan langsung pada masyarakat Aceh secara menyeluruh. Adapun maksud dari pemerintah Aceh dalam menerbitkan SE ini demi mewujudkan Aceh dalam bingkat syariat yang kaffah.
Dalam memformulasikan suatu kebijakan publik biasanya dipengaruhi oleh cara pandang masyarakat dan pemerintahan dalam memahami masalah dan memecahkannya, oleh karenanya kebijakan publik merupakan suatu konsep yang biasanya lahir dari kedua unsur tersebut, sehingga bagaimana suatu masalah diangkat dan dipahami tentu berdasarkan suatu paradigma untuk dapat membangun suatu konsep.
Dalam hal ini, Aceh tentu menjadikan syariat Islam sebagai dasar pemikirannya, sehingga segala hal yang dianggap menghalangi proses penguatan syariat Islam dianggap sebagai masalah. Namun perlu diketahui, masalah dalam kebijakan publik begitu banyak macam, variasi, dan intensitasnya.
Oleh karena itu, tidak semua masalah bisa melahirkan suatu kebijakan publik. Hanya masalah publik yang dapat menggerakkan orang banyak untuk ikut memikirkan dan mencari solusi yang bisa menghasilkan sebuah kebijakan publik (only those that move people to action become policy problems). Jadi, proses perumusan masalah dalam kebijakan publik merupakan hal yang esensial dalam proses kebijakan publik.
Berkenaan dengan SE gubernur, poin dasar kebijakan tentang aturan yang memuat didalamnya sebenarnya perlu dipetakan, apakah kebijakan yang dihasilkan dari SE ini berdasarkan masalah publik sesuai dengan intensitasnya sebagai masalah publik atau hanya sekedar kekhawatiran yang masih bisa dilakukan alternatif lain. Kalaupun usulan kebijakan ini merupakan masalah publik, yang menjadi tanda tanya mengapa banyak masyarakat yang memiliki kesan bahwa aturan ini tampak berlebihan sehingga menimbulkan pro-kontra. Tentu ada berbagai macam penyebab, mulai dari kecacatan bentuk kebijakannya hingga penolakan esensi kebijakan itu sendiri.
Terlepas dari masalah teknis SE ini yang terlihat tidak memiliki kedudukan hukum mengikat sehingga posisinya dapat dikatakan sebagai hal yang ‘makruh’ secara hukum, artinya “dilakukan bagus menurut pemerintah, namun tidak berdosa jika dilanggar” sebab kebijakan yang dikeluarkan hanya berupa Surat Edaran bukan produk hukum seperti pergub ataupun qanun. Kita perlu melihat secara esensial bahwa pada tataran ideologis sebenarnya tampak ada problem filosofis terkait perbedaan cara pandang tentang keislaman masyarakat Aceh, sebab tidak sedikit kalangan menilai beberapa rincian yang memuat aturan sesuai dengan syariat Islam namun tidak disetujui, seperti pengaturan jam malam pada warkop hingga larangan berboncengan yang bukan mahrom.
Perbedaan ini barangkali tidak serta merta lahir dari perdebatan pikiran biasa, Bisa jadi, hal ini merupakan tanda bahwa masih banyak masyarakat yang belum teredukasi sepenuhnya tentang nilai keislaman itu sendiri atau tidak menutup kemugkinan bahwa pemerintah juga tidak memiliki pemahaman yang cukup baik dalam mengomunikasikan ide syariat pada masyarakat. Bila kita mau sadar dan merefleksikan bersama, memang ada banyak tantangan dalam proses islamisasi kebijakan, penyebabnya tidak lain adalah tantangan zaman yang kita hadapi dari dunia luar dan minimnya penguatan keyakinan keagamaan pada masing-masing individu. Sehingga, hal ini tentu memicu banyak konsekuensi logis pada pikiran masyarakat yang seolah tidak sepakat tentang ide syariat ditataran kebijakan.
Polemik kebijakan tentang penguatan Syariat Islam sebenarnya bukan yang pertama kalinya, sebelum pengangkatan masalah yang terakomodasi dalam SE ini, Aceh juga pernah mengalami polemik tentang maraknya game online yang dinilai memiliki dampak buruk sehingga keluarlah fatwa haram dari ulama beserta rinciannya, serba-serbi larangan konser dan tempat hiburan seperti bioskop yang dinilai akan mengancam tujuan penguatan syariat Islam di Aceh juga menjadi topik yang bersliweran dikalangan masyarakat.
Berdasarkan fenomena ini, tampaknya kita perlu berbenah terkait arah syariat yang ingin kita capai dari segi komprehensifitasnya. Sebenarnya, ada banyak persoalan yang harus didahulukan untuk dapat mewujudkan aceh dalam bingkai syariat. Sebab makna syariat sendiri begitu luas dalam aplikasinya. Setidaknya pemerintah dapat memetakan berbagai masalah yang dihadapi aceh dimulai dari yang terbesar hingga yang terkecil, seperti persoalan pendidikan, kemiskinan, lapangan kerja, dan kesehatan adalah hal sentral harus diperhatikan sebelum faktor penunjang lain seperti tatanan sosial yang bisa jadi merupakan konsekuensi logis dari buruknya pengelolaan dari beberapa aspek tersebut.
Dimensi inilah yang seharusnya diprioritaskan tanpa melupakan pentingnya dimensi syariat pada aspek sosial kemasyarakatan. Dengan demikian, saat sumber daya manusianya sudah cukup mumpuni, dan kemudian pemerintah menerbitkan peraturan yang sesuai dengan Syariat Islam, masyarakat tidak akan merasa keberatan dengan pemahaman yang sudah baik serta ekologi yang mendukung. Jadi, kebijakan seharusnya tidak sekedar melalui metode preventif dan represif atas suatu masalah sosial, hendaknya pemerintah juga memastikan bahwa pemahaman yang diberikan kepada masyarakat dan faktor pendukung lainnya cukup baik sebagai penunjang ekologi sosial masyarakat.
Tak berhenti sampai disitu, pemerintah juga harus memiliki pemahaman yang cukup terhadap teori dan konsep dalam perumusan suatu kebijakan. Jangan sampai pemangku kebijakan juga tampak tidak terdidik dengan begitu baik dalam menetapkan kebijakan, sehingga arah yang ingin dicapai seperti mimpi di siang bolong. Menginginkan pengingkatan syariat, tapi sebenarnya tidak begitu siap.
Penulis: Alumni Ilmu Pemerintahan USK, Satria Gunawan S. IP
Berita Populer









 Sebelumnya
Sebelumnya









