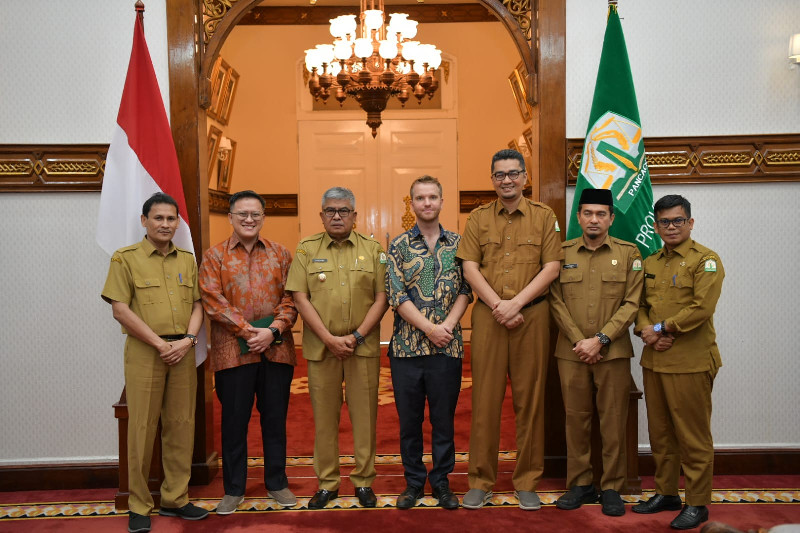Sepeda dan Perempuan
Font: Ukuran: - +

Sepeda saat ini bukan lagi alat untuk berolahraga di era pascamodern ini. Ada banyak hal yang berubah drastis dan ikut mengubah perilaku dan cara berpikir manusia. Peradaban modern ini ditandai dengan mengembangnya suatu fenomena budaya dengan cepat, secepat ia mengempis. Tata nilai tunggang-langgang, melesat, dan kemudian hilang. Seperti istilah dari sosiolog, Anthony Giddens, runaway world!
Salah satu contoh yang menunjukkan pernyata tersebut adalah fenomena bitcoin. Bitcoin adalah mata uang digital yang tidak tergantung pada mata uang konvensional. Diciptakan pada 2010 oleh seorang Jepang, Satoshi Nakamoto. Harga awalnya ketika diluncurkan hanya 0,1 USD atau Rp. 1.300 saja. Namun, tujuh tahun kemudian harganya melejit menjadi 19.340 dollar atau Rp. 261 juta.
Fetisisme komoditas
Sebenarnya bukan hanya tentang bitcoin atau Steemit - super blog yang menggunakan bitcoin sebagai nilai tukarnya - yang membuat banyak orang termehek-mehek pada objek barang. Manusia modern kerap melakukan “ritual belanja” hingga di luar nalar. Saat ini yang sedang booming adalah membeli sepeda mahal sebagai budaya olahraga baru, setelah budaya beli tas mahal menyergap hati perempuan-perempuan kelas menengah.
Jika sebelumnya kelompok artis dan kaum sosialita membeli tas Hermes, Chanel, Louis Vuitton, Gucci, atau Prada, untuk gengsi kelas, kini kelas menengah laki-laki sedang gandrung mencari “kereta angin” bermerek mahal seperti Santa Cruz, Trek, Yeti, Specialised, atau Giant. Dibandrol dari harga belasan hingga ratusan juta rupiah. Bahkan jika kita seluncur di internet, ada harga sepeda hingga puluhan miliar rupiah! Padahal kebanyakan yang mengggunakan bukan atlet selevel Pawel Poljanski atau Lance Amstrong, tapi hanya pemula.
Kegilaan itulah dalam kajian budaya disebut sebagai fetisisme komoditas. Konsep yang dimunculkan pertama sekali oleh Karl Marx dan kemudian dikembangkan oleh Louis Althusser ini menjelaskan bagaimana manusia terikat pada pemujaan benda-benda sehingga menjadikan barang-barang dan gaya sebagai identitas dirinya.
Marx sebagai pemikir pertama yang mengkritik kapitalisme hingga ke akar, memasukkan konsep fetisisme sebagai sesuatu yang menjerumuskan manusia pada mendehumanisasi. Barang dibeli bukan lagi pada keperluan, tapi sebagai kesenangan (desire) dan pemupukan ego. Pemilik barang menjadi borjuis kecil di tengah pemilik raksasa modal (La petite bourgeoisie). Konsumsi barang bukan lagi pada aspek fungsionalnya, tapi pada aspek simbolis, iklan, wacana publik, dan citra diri.
Akhirnya sepeda menjadi tren sosial saat ini. Duduk di café yang didiskusikan sepeda. Sepeda sedang diparkir ditaksir harganya. Sepeda “dikaji” dihubungkan sebagai satu-satunya cara berolahraga. Sepeda menjadi objek keinginan (object of desire) dan masuk ke dalam ideologi konsumerisme yang ikut ditransmisikan di media sosial dan digital.
Sepeda menjadi regulasi
Hingga akhirnya sepeda masuk ke dalam regulasi politik. Ceritanya berawal ketika kebijakan Wali Kota Banda Aceh melarang bersepeda bagi perempuan tak berjilbab.
Bagi yang tidak paham konteks kebijakan tersebut, pasti bertanya-tanya, apa pula urusan wali kota mengurus pakaian perempuan pesepeda, harus berjilbab. Dan ketika harus berhijab, model seperti apa lagi yang harus digunakan? Merek apa dan ukuran apa? Ia mungkin lupa bahwa Banda Aceh adalah melting pot Aceh sejak 500 tahun lampau, dikenal sebagai kota keberagaman.
Hasil penelitian penulis tentang keberagaman Koetaradja menunjukkan Banda Aceh adalah kota yang ramah terhadap beragam etnis/ras dari Asia dan Eropa, termasuk agama-agama dunia, bukan hanya Islam. Sejarah Hinduisme sejak abad kesembilan ikut memarnai juga kota ini. Migrasi Tionghoa, terutama dari Khek dan Hokkian, telah berlangsung paling sedikit sejak abad 13 hingga 1950-an telah membentuk pecinan yang bernama Peunayong. Di kota ini ada empat gereja besar dan vihara berdiri. Maka siapapun yang menjadi wali kota Banda Aceh harus bisa menghirup akar pluralisme dan multikulturalisme kota.
Namun penulis paham, reaksi sang wali kota ternyata dipengaruhi oleh video sekumpulan perempuan muda (cantik?) yang bersepeda dan mengambil hotspot di beberapa sudut kota. Penulis merasa, pasti sang wali kota menjadi panas hati ketika ada yang men-share video itu kepadanya sehingga akhirnya dalam tempo secepatnya, di tengah ketidakstabilan emosi, terburu-buru membuat kebijakan, dan sayangnya tidak populis. Berita berbahasa Inggris tentang wali kota Banda Aceh melarang bersepeda yang tidak berpakaian muslim, telah memberikan opini negatif. Berita negatif dan sensasional memang mudah terbang ke mana-mana.
Padahal ketika diteliti, sang perempuan itu tak ada yang memakai celana pendek, dan sebagian tetap berjilbab. Mungkin kecentilan mereka yang mengganggu. Pertanyaannya, apakah sebuah regulasi bisa dibuat berbasis ekspresi centil atau manja? Apakah tubuh perempuan layak diperbincangkan serampangan oleh mata laki-laki yang nanar dan menuduh mereka biang perusak Syariat? Namun di sisi lain ada pelanggaran Syariat yang lebih parah lagi (yang umumnya dilakukan oleh laki-laki dan bekuasa) seperti perusakan lingkungan dan hutan kota, korupsi, pelecehan seksual, pemerkosaan, tata pemerintahan buruk sehingga melahirkan kemiskinan dan kebodohan. Ada masalah yang lebih besar yang “merusak” tapi tidak pernah diperhatikan dengan seterburu-buru perempuan bersepeda.
Akhirnya terlihat, bahwa perempuan dan sepeda adalah sama dalam konteks purnamodern. Keduanya masuk dalam market settlement, problem-problem pasar yang dikomodifikasi oleh pemilik modal, dan kemudian meningkat “nilainya” melebihi fungsinya, mengikuti hasrat instingtif berbelanja dan gejolak libidinal. Seolah-olah ketika ia konsumtif maka dia eksis. “I shop therefore I exist”.
Perkembangan media, termasuk media sosial seperti youtube dan tiktok telah memengaruhi cara pandang pemilik modal (kelas menengah) dan kebijakan untuk menjadikan hal-hal yang ditonton menjadi penting dianalisis. Padahal itu masalah remeh dan dangkal semata. Prof. Ariel Heryanto, profesor The Australian National University, menilai perkembangan media pascaSoeharto cenderung beragam, tapi mempertontonkan masalah dangkal, superfisial, dan hiburan picisan. Jarang ada yang memotret kehidupan riil dari sosio-kultural masyarakat. Liberalisasi dan multiplikasi media telah mendorong persaingan tayangan yang sarat sensasi (Visia Ita Yulianto dalam Ariel Heryanto (ed), Budaya Populer di Indonesia : Mencairnya Identitas Pasca-Orde Baru, 2012). Biar aneh dan dungu, yang penting ditonton.
Akhirnya, perempuan bersepeda itu pun harus menjadi perhatian elite politik se-Aceh. Kasihan, sepeda dan perempuan, hanya menjadi objek domestifikasi, komersialisasi, dan subordinasi para lelaki berduit. Terjadilah politisasi penimpaan kesalahan, lupa refleksi diri, dan melihat kerusakan yang telah kita sumbangkan pada semesta.
Penulis: Teuku Kemal Fasya, antropolog Unimal.
Berita Populer







 Sebelumnya
Sebelumnya